
Mengawali tahun 2025, Presiden Prabowo baru saja menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang akan memaksa efisiensi di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Instruksi Presiden ini (atau executive order di Pemerintahan Trump) telah mengejutkan banyak pihak. Ia bisa menjadi sebuah game changer, yaitu walaupun Prabowo mengangkat begitu banyak menteri, tetapi mengendalikan anggaran dalam satu komando. Para politisi tidak mudah lagi korupsi dan memanipulasi anggaran negara dan daerah.
Instruksi Presiden tersebut juga telah mematahkan mitos
rezim perencanaan dan penganggaran yang sudah begitu lama berkuasa di negeri ini. Selama ini, setelah disahkan, rencana dan anggaran ibarat kitab suci yang tidak bisa diubah dengan mudah, tetapi harus melalui berbagai prosedur yang berbelit, kaku, dan birokratis.
Mitos yang berhasil dikembangkan rezim perencanaan dan penganggaran tersebut adalah rencana dan anggaran harus disusun secara sistematis untuk dapat mengendalikan pembangunan nasional dan daerah.
Itu sebabnya, unit atau fungsi perencanaan dan penganggaran begitu berkuasanya di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah setelah reformasi keuangan dikumandangkan dengan Undang-Undang Keuangan Negara tahun 2003 dan diikuti dengan Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2004.
Pada kenyataannya, rencana dan anggaran di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah lebih banyak hasil dari tekanan politik dan regulasi yang kaku, seperti untuk menampung kepentingan aspirasi dan pokok pikiran politisi daripada melakukan pembangunan untuk kepentingan masyarakat. Itulah sebabnya, nilai rupiah ketidakefektifan dan ketidakefisienan rencana dan anggaran tersebut begitu tingginya di Indonesia, sebagaimana terungkap di berbagai media.
Karena itu, tindakan dramatis Prabowo dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 perlu diacungi jempol, walaupun kemudian memunculkan berbagai perlawanan, baik dari para politisi maupun birokrat. Melalui pernyataan para pakar, di sebuah media besar, mereka sudah mulai berani menyatakan bahwa Instruksi Presiden Prabowo tersebut melawan hukum.
Sebenarnya, Instruksi Presiden tersebut pada dasarnya
mengingatkan memori kita tentang keberhasilan revolusi Mao Zedong ketika memandirikan Tiongkok. Waktu itu, Mao berhasil mengubah bangsa Tiongkok yang dominan sebagai konsumen dunia berubah menjadi produsen dunia.
Sebagai negara post-kolonialis, Indonesia pun sudah sejak lama dikondisikan sebagai bangsa konsumen daripada bangsa produsen. Dengan jumlah penduduknya yang besar, Indonesia dibentuk oleh para kolonialis menjadi konsumen berbagai produk negara-negara lain di dunia ini. Indonesia kemudian menjadi sangat tergantung pada produk negara lain.
Pertanyaannya, akankah Indonesia berhasil menjadi bangsa produsen dengan Instruksi Presiden tersebut? Atau, apakah Instruksi Presiden tersebut hanyalah utopia untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang mandiri?
Pengantar dari redaksi ini akan membuka perdebatan tersebut.
Revolusi Mao Zedong
Revolusi Mao Zedong, yang dikenal sebagai “Revolusi Komunis Tiongkok”, telah menjadikan Tiongkok sebagai negara produsen besar dunia. Pada waktu itu, ia mengenalkan Reformasi Agraria.
Setelah berkuasa pada tahun 1949, Mao mereformasi agraria secara signifikan, yaitu tanah milik para tuan tanah diambil alih dan kemudian dibagikan kepada para petani miskin.
Tindakan Mao itu tidak hanya berhasil meningkatkan produksi pertanian, tetapi juga menciptakan loyalitas para petani terhadap pemerintah komunis di Tiongkok.
Kedua, Gerakan Koperasi dan Komunal. Pada 1950-an, Mao mempromosikan gerakan koperasi pertanian yang kemudian berubah menjadi komune rakyat, yaitu semua aset produksi dikelola secara kolektif. Meskipun awalnya menghadapi banyak kesulitan, hal ini menjadi dasar pengelolaan sumber daya yang efisien.
Ketiga, Kebijakan “Great Leap Forward”. Meskipun waktu itu dikenal sebagai periode bencana karena memunculkan kelaparan besar, ide dasar kebijakan ini berhasil meningkatkan produksi industri dan pertanian secara simultan.
Meskipun gagal dalam banyak aspek, kebijakan tersebut berhasil menanamkan ide-ide industrialisasi Tiongkok yang kemudian dikembangkan setelah kematian Mao.
Keempat, Industrialisasi. Setelah kebijakan “Great Leap Forward“, Tiongkok kemudian fokus pada industrialisasi melalui rencana lima tahun yang lebih terarah, termasuk pembangunan infrastruktur industri baja dan tekstil.
Kelima, Penguatan Pendidikan dan Keterampilan. Mao mendorong pendidikan massal. Walaupun terbatas dalam hal kualitas, hal ini memberikan dasar keterampilan yang luas bagi rakyat Tiongkok untuk mendukung pertumbuhan industri.
Keenam, Penguatan Mobilitas Sosial dan Pembangunan Infrastruktur, yaitu pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, rel, dan energi yang memungkinkan mobilitas sosial dan ekonomi yang lebih tinggi, yang kemudian mendukung produksi.
Setelah kematian Mao, Deng Xiaoping meneruskan reformasi ekonomi pada akhir 1970-an dan 1980-an. Reformasi ini termasuk membuka Tiongkok ke pasar internasional, penciptaan Zona Ekonomi Khusus (SEZ), dan melakukan transisi dari ekonomi terpusat ke ekonomi yang lebih terbuka dan berorientasi pasar.
Rezim Efisiensi versus Efektivitas
Sebelum lebih jauh membahas efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 1/2025, kita harus memahami “rezim efisiensi”, yang secara umum mengacu pada peningkatan efisiensi proses, produksi, ataupun pengelolaan sumber daya.
Efisiensi berarti melakukan sesuatu dengan sedikit atau tanpa pemborosan sumber daya, baik itu waktu, tenaga kerja, bahan baku, atau modal. Intinya, efisiensi adalah tindakan yang dirancang untuk memaksimalkan keluaran dengan masukan yang seminimal mungkin.
Dalam dunia bisnis, efisiensi berarti implementasi berbagai strategi, seperti Lean Manufacturing, Six Sigma, atau Total Quality Management (TQM), yang semuanya ini bertujuan untuk mengurangi pemborosan, meningkatkan kualitas produk, dan mempercepat proses produksi.
Efisiensi juga mencakup otomatisasi, penggunaan teknologi informasi untuk optimalisasi proses, dan pengelolaan sumber daya manusia yang lebih efisien.
Di tingkat makro, efisiensi berkaitan dengan kebijakan ekonomi yang mengoptimalkan alokasi sumber daya, seperti kebijakan fiskal untuk menghindari pemborosan anggaran negara ataupun kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi, tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi.
Meskipun sering dikaitkan dengan ekonomi, efisiensi memiliki implikasi sosial, seperti pekerjaan yang diotomatisasi mempengaruhi lapangan kerja atau efisiensi layanan publik meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Di pendulum yang lain, “rezim efektivitas” merujuk pada pencapaian hasil atau tujuan yang diinginkan dengan cara yang paling efektif.
Berbeda dengan rezim efisiensi, rezim efektivitas lebih menekankan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan, tidak peduli berapa banyak sumber daya yang digunakan.
Intinya, efektivitas adalah tentang seberapa baik kita mencapai tujuan
atau hasil yang diinginkan, yang dirancang untuk memastikan bahwa strategi, kebijakan, atau aktivitas yang diterapkan benar-benar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Dalam dunia bisnis, efektivitas berarti penilaian kinerja proyek atau divisi berdasarkan pencapaian target, seperti target penjualan, kepuasan pelanggan, atau inovasi. Hal ini mencakup pengembangan metrik efektivitas, evaluasi kinerja, dan penyesuaian strategi untuk memastikan tujuan bisnis tercapai.
Pada sektor publik, rezim efektivitas adalah evaluasi kebijakan publik berdasarkan seberapa baik kebijakan mencapai tujuan sosial, ekonomi, atau politik. Misalnya, efektivitas program kesehatan diukur dari perbaikan kesehatan masyarakat, bukan hanya dari efisiensi penggunaan anggaran.
Meskipun tidak selalu berhubungan langsung dengan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, dalam rezim efektivitas, penggunaan sumber daya bisa diterima jika hasil yang dicapai sesuai atau melebihi harapan.
Untuk mencapai dan mengukur efektivitas, sering kali menggunakan berbagai metode, seperti penelitian evaluatif, analisis hasil, umpan balik dari pemangku kepentingan, dan audit kinerja. Key Performance Indicators (KPI) dan metrik lainnya biasanya digunakan untuk memantau dan menilai efektivitas.
Belakangan, kemudian terdapat pendekatan yang mencoba menyeimbangkan efektivitas dengan efisiensi, yaitu sumber daya digunakan dengan cara yang efektif tanpa pemborosan yang berlebihan. Dalam konteks ini, efektivitas adalah syarat mutlak untuk bisa mengklaim bahwa suatu organisasi sudah efisien.
Efisiensi, Efektivitas, dan Reformasi Birokrasi
Setelah kejatuhan Presiden Soeharto, Pemerintah Indonesia terus mempromosikan reformasi birokrasi, sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
Dalam narasi formal, reformasi diklaim akan memangkas birokrasi yang berbelit, meningkatkan pelayanan publik, dan mempercepat pengambilan keputusan strategis.
Pada praktiknya, reformasi birokrasi yang dijalankan sering kali lebih condong pada pengurangan jumlah pegawai, pemotongan anggaran, dan digitalisasi, tetapi tanpa perbaikan signifikan dalam mekanisme kerja yang lebih produktif.
Contohnya, alih-alih memangkas anggaran riset dan pendidikan, Pemerintah mestinya mengurangi jumlah menteri dan kementerian, mengefisienkan pengadaan barang dan jasa yang tidak perlu, memangkas regulasi yang menghambat investasi, serta mempercepat proses perizinan di sektor-sektor strategis.
Ironisnya, di tengah upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi
melalui reformasi birokrasi, banyak kebijakan pemerintah yang justru menghambat berjalannya pembangunan nasional dan daerah.
Sebagai contoh, proyek infrastruktur sering terhambat
karena rezim perencanaan dan penganggaran yang kaku, yang kemudian mengakibatkan pelaku usaha kesulitan mengakses insentif, regulasi yang tumpang tindih, inovasi nasional tidak berkembang, dan birokrasi perizinan berorientasi pada kontrol, bukan fasilitasi.
Jika kondisi tersebut terus dibiarkan, maka visi Indonesia Emas 2045 tidak lebih dari sekadar jargon politik, dengan birokrasi menjadi penghambat utama mencapai kemandirian bangsa.
Dampak Efisiensi Instruksi Presiden terhadap Birokrasi
Kebijakan efisiensi pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 telah memaksa kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mau beradaptasi dan bekerja secara agile. Di antaranya, mereka mulai menghemat biaya operasional, seperti biaya perjalanan dinas, listrik, internet, dan lembur.
Pendingin ruangan dan lampu pun mulai dinyalakan sebagian, konsumsi rapat dibatasi, serta makan-minum di kantor dikurangi. Kemudian, muncul keluhan aparatur sipil negara (ASN) di media sosial dengan berbagai lelucon yang sarkastis.
Menyikapi hal itu, beberapa pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mulai bertindak. Sebagai contoh, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) melarang ASN berkeluh kesah di media sosial dan menghindari komentar mengenai Instruksi Presiden tersebut.
Secara patriotik, seorang menteri pun mengingatkan bahwa di awal kemerdekaan dulu, para penyelenggara negara harus dapat bekerja tanpa mengandalkan anggaran dari negara.
Pernyataan para elite tersebut menarik diperhatikan. Memang, kesulitan dan tantangan tidak akan menghancurkan kelompok, organisasi, atau sebuah entitas.
Malah sebaliknya, hal ini bisa memunculkan kreativitas dan kebersamaan. Kita bisa lebih kuat menghadapi berbagai kesulitan di masa depan.
Syaratnya, semua pihak merasakan hal yang sama. Kebersamaan akan memunculkan solidaritas. Tanpa kebersamaan, jangankan kesulitan, hasilnya adalah perpecahan, perselisihan, dan kehancuran.
Itu sebabnya, mereka yang tidak terkena langsung dampak efisiensi harus menunjukkan empatinya. Sebagai contoh, mereka bisa diminta untuk menyumbangkan hartanya ke negara secara sukarela.
Kita tentu tahu bahwa beberapa elite militer dan kepolisian memiliki harta pribadi yang tidak terbatas. Presiden Prabowo harus mau mengerahkan mereka untuk menyumbangkan hartanya, seperti dulu zaman Presiden Soeharto meminta elite menyumbangkan emasnya ke Pemerintah ketika krisis moneter melanda.
Dengan demikian, harapan agar birokrasi mau menyikapi kebijakan ini dengan positif, sebagaimana yang diharapkan para elite birokrasi, tidak menjadi isapan jempol belaka.
Epilog: The Power of “Kepepet”
Menurut teori evolusi, makhluk hidup akan terus menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk tetap bertahan hidup. Manusia mampu menyesuaikan diri tidak hanya pada kemampuan fisiknya, tetapi juga pada kemampuan berpikir dan bersosialisasi.
Manusia memiliki kemampuan untuk belajar, berinovasi, dan bekerja sama, yang memungkinkan mereka menyesuaikan diri dengan berbagai hal, termasuk ketika terjadi keterbatasan sumber daya.
Sifat inovatif manusia merupakan adaptasi terhadap perubahan lingkungan internal maupun eksternal. Ketika menghadapi tantangan atau keterbatasan, manusia akan lebih kreatif dan menemukan cara untuk bertahan hidup dan mencapai apa yang mereka inginkan.
Karenanya, dalam implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, inovasi menjadi kata kunci yang sangat penting. Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang beradaptasi dengan cepat akan bertahan dan kemudian berhasil menciptakan kemandirian bangsa.
Apakah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 akan menciptakan kemandirian bangsa atau hanya sekadar utopia? Ini tergantung Anda semua.
Karenanya, silakan memberikan tanggapan atas pengantar redaksi ini.
***

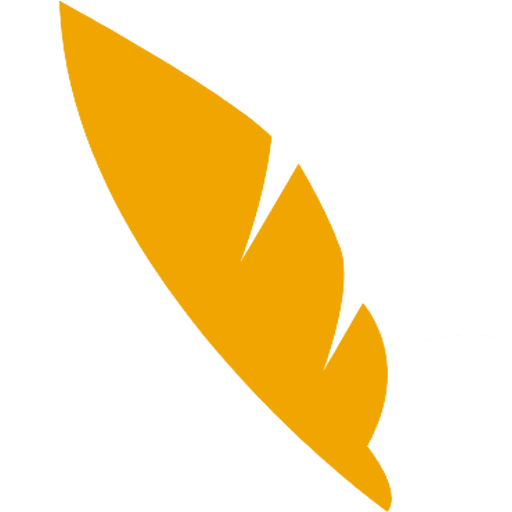













0 Comments