
Pemilu Ulang di 26 Kabupaten
Senin 24 Februari 2025, Mahkamah Konstitusi melalui sembilan hakimnya menyampaikan keputusan untuk melakukan rekapitulasi ulang di Pemilu Kada di 26 kabupaten di Indonesia. Putusan ini adalah beberapa keputusan yang ditetapkan MK dalam rangka perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tahun 2024.
Secara umum terdapat 310 permohonan
terkait pemilu kepala daerah pada tahun 2024 kemarin yang masuk ke meja Mahkamah Konstitusi. Keputusan ini menandai rampungnya penyelesaian seluruh permohonan tersebut.
Menyikapi hal ini, salah satu anggota DPR RI menyampaikan keprihatinannya terhadap kualitas Pemilu Tahun 2024 tersebut. Beliau dengan menggebu bahkan menyampaikan bahwa kualitas Pemilu Tahun 2024 adalah pemilu paling rusak yang pernah ada.
Menariknya, beliau menyampaikan hal tersebut dengan membandingkan beberapa fakta, di antaranya tentang fakta bahwa terdapat 310 daerah yang pemilu kada-nya bermasalah. Terdapat juga 37 pemilu yang dilaksanakan dengan “kotak kosong”. Hal tersebut berarti kurang dari setengah daerah yang pemilunya tidak bermasalah.
Di sisi yang lain, beliau juga menambahkan bahwa sisa Pemilu Kepala Daerah yang tidak dilakukan pengajuan sengketa kepada MK tersebut juga tidak bisa diambil kesimpulan sebagai pemilu yang tak bermasalah karena faktor lain bisa saja menjadi penyebabnya. Faktor tersebut bisa jadi kebosanan, kelelahan, atau ketidakpercayaan.
Keprihatinan terhadap kualitas pemilu di Indonesia tersebut tentu tidak tanpa alasan. Kualitas pemilu kepala daerah tentu akan sangat berpengaruh terhadap legitimasi dan kualitas pemimpin yang akan memimpin daerah.
Jika legitimasi dan kualitasnya rendah, maka jangan harapkan suatu daerah akan maju atau berhasil. Di sisi yang lain, keputusan mengulang pemilu di beberapa daerah sebagaimana isi keputusan MK akan membebani rakyat kembali dengan anggaran operasionalnya yang tidak sedikit.
Perjalanan Demokrasi (Menuju Kedaulatan Rakyat)
Demokrasi di Indonesia sudah berjalan cukup panjang. Semenjak pendiriannya, negara ini sudah memaktubkan dirinya sebagai negara demokrasi. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.
Dalam praktiknya, demokrasi di Indonesia telah melalui perjalanan sejarah dan berganti-ganti pada setiap masanya. Mulai dari demokrasi parlementer antara tahun 1945–1959. Kemudian berganti menjadi terpimpin di periode 1959–1965. Lantas Demokrasi Pancasila semasa Orde Baru 1965–1999. Dan saat ini Indonesia berada di masa Demokrasi Reformasi.
Beberapa kalangan menganggap bahwa demokrasi di masa reformasi ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dibandingkan masa-masa sebelumnya. Hal ini karena dalam demokrasi reformasi ini kita diperkenalkan dengan pemilihan secara langsung, inklusivitas rekrutmen politik, pemenuhan hak dasar politik yang terjamin, dan adanya desentralisasi politik.
Berbicara demokrasi, sesungguhnya tidak hanya berbicara rekrutmen politik dalam bentuk pemilu semata, melainkan meliputi berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara secara umum. Bagaimana negara dan pemerintahan berjalan?
Apakah otoriterian atau demokratis adalah bagian dari demokrasi. Apakah negara berada di atas rakyat atau sebaliknya atau sama rata, adalah bagian dari itu. Bagaimana kebebasan masyarakat dalam berkumpul dan menyampaikan pendapat, juga merupakan bagian dari demokrasi.
Namun begitu, kualitas rekrutmen politik (pemilu) tentu dapat menjadi salah satu indikator dari pelaksanaan demokrasi di suatu negara. Oleh karena itu, jika asumsinya demokrasi reformasi ini lebih baik dari masa-masa sebelumnya, seharusnya kualitas pemilu saat ini haruslah lebih baik dari masa sebelumnya.
Baik dari seluruh faktornya tentunya. Mulai dari prosesnya sampai pada kualitas hasilnya.
Lantas apakah benar pemilu Indonesia kemarin atau saat ini sedang dalam level yang rusak sebagaimana disampaikan oleh salah satu anggota DPR RI di atas?
Sebagai ASN yang berada di level terendah dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia yakni kecamatan, penulis memiliki persepsi sendiri tentang hal itu. Persepsi tersebut tentu saja persepsi di level akar rumput (grassroot). Level yang mungkin sebagian orang menganggapnya remeh, tidak dapat digeneralisasi.
Namun, seremeh apa pun posisi dan wilayah kerja penulis dalam sistem politik nasional, mudah-mudahan tidak mengurangi kepekaan para pemimpin nasional untuk menangkap fenomena ini dan melakukan upaya untuk memberikan solusi terbaik dalam rangka perbaikan sistem pemilu di Indonesia.
Menakar Kualitas Pemilu dari Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
(Suara dari Akar Rumput)
Demokrasi yang baik harus ditopang oleh pemilu yang jujur dan adil. Dalam kacamata penulis, pemilu jujur adalah pemilu yang berjalan secara alami tanpa rekayasa dan tanpa manipulasi. Ia berjalan sesuai kehendak masyarakat banyak.
Sementara adil bermakna pemilu memberi kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk terlibat, baik sebagai pemilih aktif maupun yang dipilih.
Dalam konteks pemilu di Indonesia terutama pasca reformasi, penulis skeptis tentang masih adanya pemilu yang jujur dan adil di Indonesia. Karena jangankan pada pelaksanaan pemilihan tingkat nasional yang memperebutkan akses kekuasaan yang besar, bahkan dalam pemilihan tingkat desa pun sulit sekali ditemukan pemilihan yang menggambarkan kejujuran dan keadilan.
Berkenaan dengan pemilihan kepala desa (Pilkades), beruntung sekali penulis dipertemukan dengan pelaku sejarah pilkades-pilkades di masa lalu. Melalui obrolan warung kopi, penulis mencoba melakukan penyelidikan tentang bagaimana pimpinan desa di masa lalu diangkat.
Untuk mempertajam informasi yang diperoleh, penulis melakukan obrolan tersebut dengan beberapa orang. Setidaknya 4 orang sesepuh di wilayah penulis bekerja untuk mendapatkan gambaran objektif tentang hal tersebut.
“Wawancara” penulis memang hanya dibatasi pada kondisi pemilihan kepala desa sebelum dan pasca reformasi. Sementara itu sejarah pilkades sendiri sebenarnya telah berjalan panjang mulai dari masa kerajaan, masa kolonial, masa kemerdekaan, masa Orde Baru, hingga saat ini masa reformasi.
Namun tentu sulit sekali penulis menemukan narasumber yang menjadi pelaku sejarah masa-masa sebelum Orde Baru. Oleh karena itu, perbandingan yang paling rasional bagi penulis hanyalah antara pilkades sebelum reformasi dan sesudah reformasi.
Pilkades: Sebelum dan Sesudah Reformasi
Hasil “wawancara” penulis dengan para tokoh dan pelaku sejarah pilkades tersebut menghasilkan temuan yang cukup menarik. Hal tersebut karena ternyata perbedaan mencolok terkait proses perekrutan bakal calon hingga proses pemilihan di antara dua masa tersebut.
Pada masa sebelum reformasi,
masyarakat menetapkan seseorang menjadi bakal calon kepala desa rupanya dilaksanakan secara bottom up. Artinya, para calon yang akan dipilih disaring oleh para tokoh masyarakat terkemuka di desa tersebut. Kemudian para tokoh itu melakukan komunikasi agar yang bersangkutan “mau” untuk dicalonkan menjadi kepala desa.
Dalam menetapkan bakal calon tersebut, beberapa aspek menjadi pertimbangan para tokoh tersebut. Di antaranya adalah rekam jejak perilaku, kemampuan memobilisasi (diikuti oleh) masyarakat, serta keaktifan di kegiatan-kegiatan sosial masyarakat.
Selain itu ada pertimbangan lain yang bercorak feodal yaitu berkaitan dengan keturunan kepemimpinan. Biasanya yang dicalonkan menjadi kepala desa memiliki garis keturunan dengan mantan-mantan kepala desa.
Pasca reformasi, atribut calon kepala desa yang sebagaimana dijelaskan tersebut awalnya tetap melekat, namun seiring waktu berjalan kondisinya berubah. Pendekatannya tidak lagi bottom up melainkan top down. Mereka yang mencalonkan diri menjadi calon kepala desa bukan lagi yang “diinginkan” masyarakat, tetapi menjadi yang “ingin” menjadi kepala desa.
Kedua perbedaan tersebut kemudian menjadi pembeda pada aspek-aspek selanjutnya. Dalam rangka menarik dukungan masyarakat, calon kepala desa pada masa sebelum reformasi telah memiliki basis dukungan yang jelas sebelum pemilihan.
Sementara itu masyarakat juga memiliki fanatisme yang kuat karena semenjak awal benar-benar menjadi pengusung calon tertentu. Pada masa pasca reformasi kedua hal tersebut tidak terjadi. Calon kepala desa tertentu bisa saja belum memiliki basis massa, sementara masyarakat sendiri belum memiliki fanatisme terhadap calon tertentu.
Kedua hal tersebut membuat proses pencalonan menjadi lebih “mahal”. Untuk menarik dukungan massa, sang calon kepala desa harus melakukan upaya lebih untuk memperkenalkan diri dan menarik simpati. Walhasil, biaya kampanye selama kontestasi kepala desa membengkak.
Upaya memperkenalkan diri secara instan tersebutlah yang pada akhirnya bermuara pada terjadinya “money politics”. Harus diakui bahwa materi lebih mudah untuk membujuk ketimbang konsep atau gagasan yang bagus.
Dampak Negatif dari Kondisi Saat Ini
Dampak proses yang berubah tersebut sangatlah besar, terutama dampak negatifnya. “Mahalnya” proses kampanye menciptakan peluang “money politics” yang kuat, sehingga saat ini sangat sulit menemukan pilkades atau calon kepala desa terpilih yang tidak menggunakan politik uang.
Proses rekrutmen yang tidak berbasis bottom up menyulitkan kepala desa terpilih untuk memobilisasi masyarakat untuk kepentingan umum saat telah menjabat. Yang lebih berbahaya adalah munculnya politik pragmatisme di tengah-tengah masyarakat.
Money politics yang berjalan terus-menerus dari pilkades satu ke pilkades lainnya menciptakan mental masyarakat yang pragmatis. Mereka tidak akan lagi mementingkan kualitas, melainkan mengedepankan prinsip jual beli.
Bahkan saat ini muncul perilaku umum di tengah masyarakat yang hanya akan memilih jika diberikan “ongkos” menuju TPS. Lantas mungkinkah sistem seperti ini menciptakan kepala desa berkualitas?
Epilog: Nyata dan Reflektif
Penulis perlu menyampaikan bahwa kondisi ini juga terjadi di tempat penulis bekerja, yang notabene masih merupakan wilayah pedesaan dengan karakter paguyuban yang masih kental. Tak terbayang kondisi yang terjadi di wilayah yang lebih perkotaan dengan masyarakat patembayan yang lebih materialistis.
Kondisi pemilihan kepala desa tersebut sedikit banyak bisa dijadikan rujukan untuk menakar kualitas pemilu Indonesia di setiap level.
Jika masa sebelum reformasi (Orde Baru), di mana kecurangan terjadi secara masif di pemilu nasional, tidak memengaruhi kualitas pelaksanaan pilkades yang menjunjung kearifan lokal yang berbudaya tinggi. Apa yang terjadi di tingkat nasional jika di akar rumput saja pemilu itu begitu kotor?
Wallahu a‘lam bish-shawab

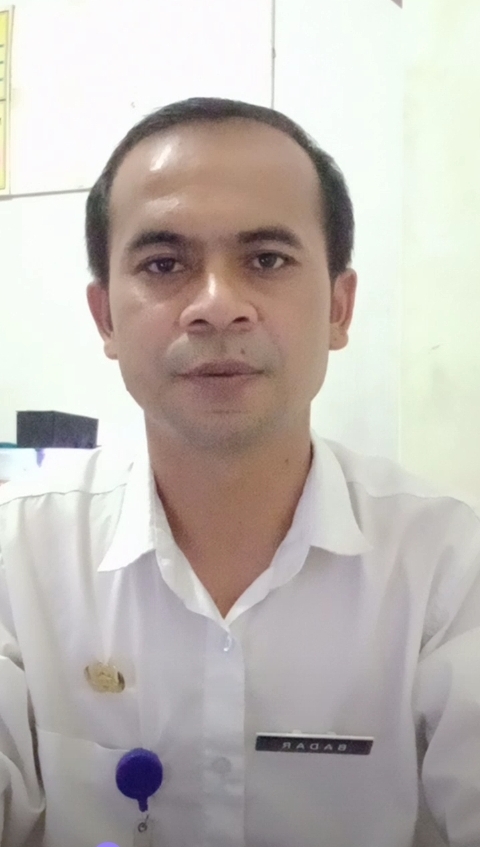













0 Comments